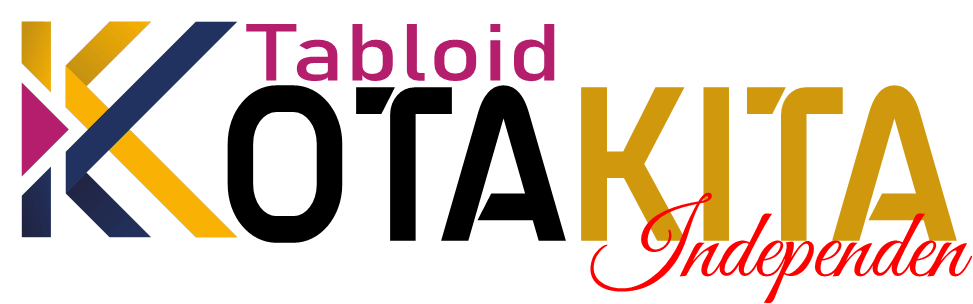Opini Politik
Oleh: Andre Vincent Wenas
Kasus mundurnya para pengurus Partai Nasdem di Indramayu yang mengundurkan diri ramai-ramai menarik perhatian luas. Hal ihwal yang melatar belakangi kasusnya bikin geleng-geleng kepala.
Jadi ini soal pencalegan, soal nomor urut caleg (calon anggota legislatif). Semuanya kepingin nomor urut 1, minimal nomor 2. Kenapa begitu? Karena sistem pemilihan dalam pemilu tahun 2024 nanti – ada isu – bakalan dilakukan dengan sistem proporsional tertutup.
Apa bedanya dengan proporisonal terbuka, seperti yang kita alami dalam pemilu 2019 lalu. Gampang, dulu kita mesti memilih figur caleg, siapa yang paling banyak dipilih konstituen maka dialah yang terpilih, yang penting partainya lolos PT (parliamentary threshold). Nomor urut caleg tidak penting lagi. Semua caleg punya kesempatan yang sama.
Sedangkan dalam sistem proporsional tertutup, pemilih hanya memilih logo partai saja, maka nomor urut caleg jadi penting. Dulu kita mengenal apa yang disebut dengan “nomor jadi” (yaitu nomor urut 1, atau 2). Caleg yang dapat nomor urut kecil punya kesempatan yang lebih besar untuk jadi.
Itu yang membuat pengurus daerah (ketua DPD) Partai Nasdem di Indramayu kecewa, lantaran ia tadinya dijanjikan nomor urut 1, tapi dalam perjalanan ternyata ia cuma dapat nomor urut di atas nomor 2. Bukan nomor jadi istilahnya. Maka murkalah ia dan segenap pengikutnya yang jadi pengurus di Indramayu.
Copot jaket partai dan segala atributnya, bikin koperensi pers, dan ini jadi berita yang dimakan berbagai media. Kancah perpolitan pra-pemilu jadi ramai. Kabarnya ada ribuan kader yang ikutan copot jaket.
Bagi sementara oknum pengurus parpol, nomor urut caleg dijadikan komoditas yang diperdagangkan, semacam dilelang begitu. Ironinya hal murahan semacam ini dilakukan bahkan oleh parpol yang selama ini menggadang jargon “anti-mahar”.
Tapi semua juga tahu bahwa walau sudah dapat nomor kecil (nomor urut 1 atau 2) tetap saja itu bukan jaminan bakal jadi. Kalau partainya ternyata tidak disukai lantaran aksi politiknya yang tidak simpatik, tentu bakal ditolak oleh rakyat. Dan sia-sialah upayanya yang telah “membeli” nomor urut tadi.
Politik dagang sapi, tapi sapinya pun cuma ilusi. Aneh memang.
Terlepas dari itu semua, memang pemilu ini tetaplah suatu pertaruhan yang menantang. Fakta politik di Indonesia telah membuktikan bahwa seorang mantan koruptor pun masih bisa terpilih. Silahkan periksa (sekarang bisa lewat google) tentang kasus koruptor yang ikut dalam pileg atau pilkada dan berhasil menang. Jadi wakil rakyat (anggota DPR/D, bupati/walikota, gubernur/wagub).
Kok bisa menang? Khan mantan koruptor?
Rupanya money-politic (politik uang), politik bagi-bagi amplop saat pemilu, masih saja menghantui kita.
Maka singkatnya dua RUU “Anti Korupsi” yaitu: RUU Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi dan RUU Pembatasan Transaksi Uang Kartal jadi imperatif.
Tanpa kedua perangkat hukum itu, parpol yang katanya berpengalaman itu kalau ditanya soal etika politik, mereka akan merespon dengan enteng:
“Berapa tuh harganya etika politik?”
Jakarta, Selasa, 13 Juni 2023
Andre Vincent Wenas,MM,MBA. Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis PERSPEKTIF (LKSP), Jakarta.